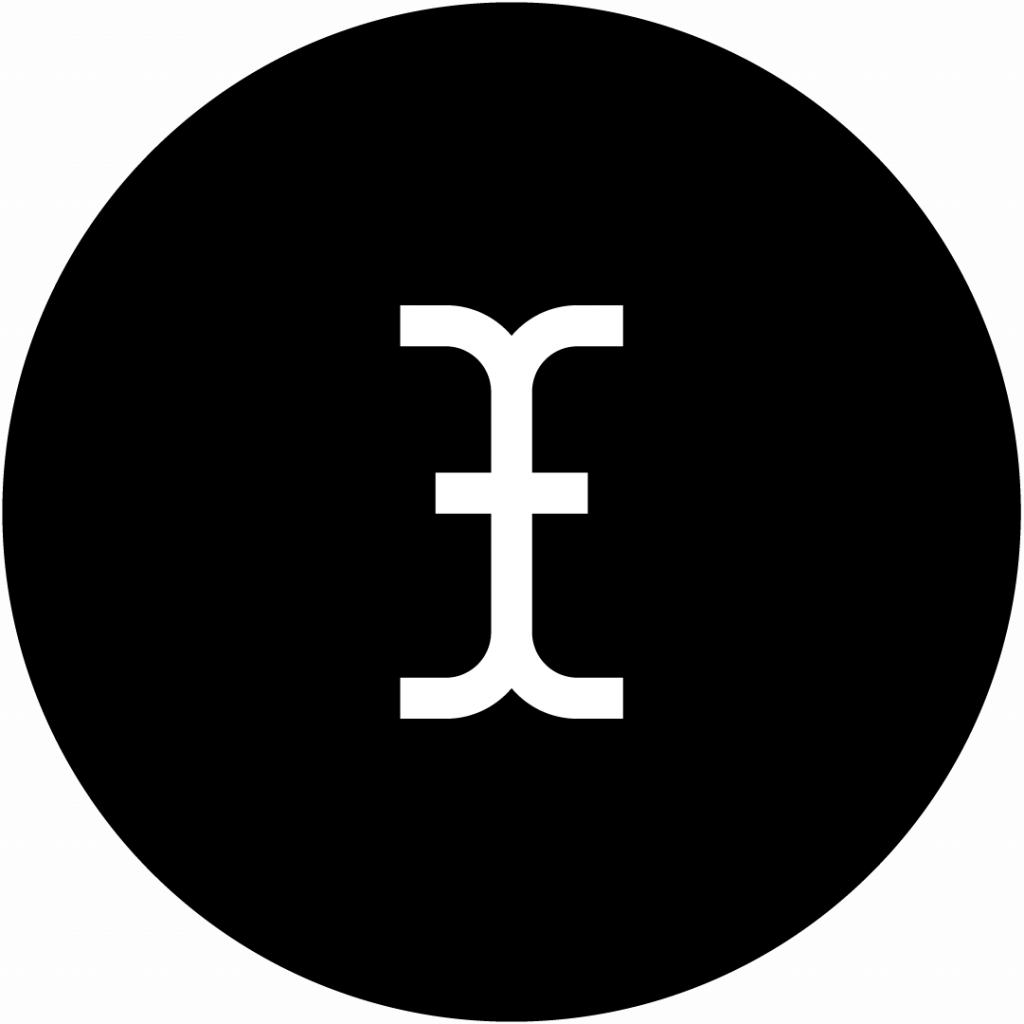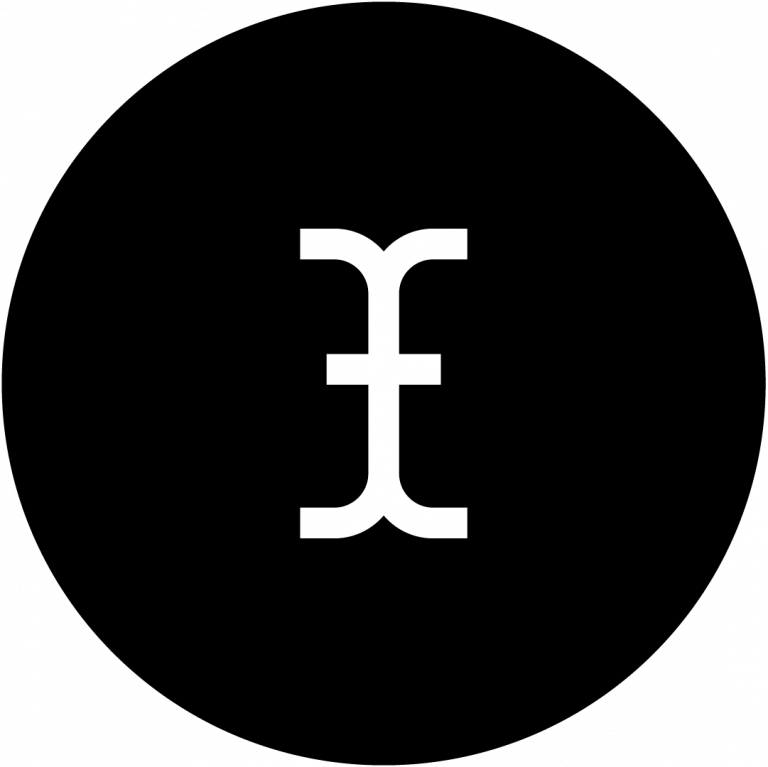Belakangan topik tentang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kian hangat—atau sengit? —dibicarakan. Terutama setelah merambah ke dunia kreatif seperti ilustrasi dan penulisan. Yang terakhir diwakili oleh penggunaan ChatGPT yang semakin gencar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan penulis karena profesi yang kini berpotensi tergantikan oleh AI atau setidaknya menurunkan daya jual mereka.
Apakah kekhawatiran akan artificial intelligence tersebut beralasan?
Sebetulnya isu mesin menggantikan tenaga kerja manusia sudah ada sejak lama. Mulai dari Industrial Revolution di abad 17 ketika peran tangan manusia perlahan diambil alih oleh mesin demi hasil output produksi lebih tinggi dan efisien.
Dan tanpa kita sadari, peran AI pun sangat marak dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan instruksi jalan Google Map hingga algoritma Netflix yang menganjurkan film atau serial televisi sesuai histori menonton.
Penggunaan mesin yang perannya lebih untuk menggantikan aktivitas manual lantas bergulir hingga teknologi artificial intelligence. Pada 1973, seniman Harold Cohen menciptakan program AARON yang mampu menghasilkan sebuah gambar dari rangkaian aturan yang telah ia tetapkan.
Lalu pada 2014, ilmuwan Ian Goodfellow menciptakan algoritma bernama generative adversarial networks (GAN) yang kini jadi prototipe sistem algoritma bagi sebagian besar kecerdasan buatan dalam bidang seni kreatif. Algoritma GAN memiliki dua “kepribadian”: yang satu berburu gambar secara acak, yang kemudian bakal difilter oleh kepribadian lainnya untuk menilai gambar mana lebih sesuai dengan input.

Seni melukis pun belakangan sudah dijamah oleh kecerdasan buatan. Baru-baru ini, rumah lelang Christie’s berhasil menjual sebuah lukisan yang murni dihasilkan oleh artificial intelligence seharga $432,500.
Lukisan bertajuk Portrait of Edmond Belamy tersebut merupakan buah pikiran trio seniman asal Paris, Hugo Caselles-Dupre, Pierre Fautrel, dan Gauthier Vernier, yang menjejali ribuan foto ke dalam sebuah algoritma dengan intensi untuk menciptakan karya yang menyerap gaya dan estetika dari foto-foto tersebut.
Tampaknya memang beberapa praktisi seni sudah siap untuk menerima kehadiran AI dalam dunia mereka. Bahkan sejumlah festival seni seperti Leicester Art AI Festival pun sudah mengangkat tema karya seni yang merupakan persilangan antara seni dan kecerdasan buatan.
Pemakaian kecerdasan buatan dalam dunia seni tentu masih diperdebatkan sampai sekarang. Para kritik mengeluhkan perkara kelemahan sebuah karya seni yang diciptakan oleh kecerdasan buatan terkait makna, orisinalitas, kreativitas, dan elemen krusial lainnya yang hanya bisa didapat apabila datang dari perpektif, pemikiran, dan pengalaman manusia di belakangnya.
Sementara para pendukung kecerdasan buatan berargumen, apabila digunakan secara bertanggung jawab, maka keterlibatan AI dalam proses menciptakan karya seni bisa membantu proses kreatif, meningkatkan produktivitas, dan mengeksplorasi inovasi yang hanya bisa dihasilkan dari kolaborasi antara seniman dan teknologi.
Penggunaan secara tanggung jawab sebetulnya merupakan hal yang mutlak dalam bidang apapun. Kecemasan kecerdasan buatan dapat menggantikan posisi manusia dalam profesi seni jelas merupakan sesuatu yang layak disorot, yang membuat negara Italia menjadi negara pertama yang melarang penggunaan ChatGPT.
Namun memang harus diingat kalau inovasi selalu terjadi dalam sejarah kehidupan manusia: mesin ketik tergantikan oleh komputer, telepon landline tergantikan oleh smartpohone, penyiaran serial televisi tergantikan oleh streaming, CD tergantikan oleh Spotify, desain manual dengan Canva, dan masih banyak lagi.
Maka sekarang tampaknya keterlibatan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya seni menjadi salah satu dari inovasi tersebut.
Lalu, kawan atau lawan? Sebetulnya masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Yang pasti, bila tidak merasa kerasan dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dalam profesi seni yang digelut, kecerdasan alami kita tetap eksis. Seperti yang tersalur dalam proses pembuatan artikel ini.