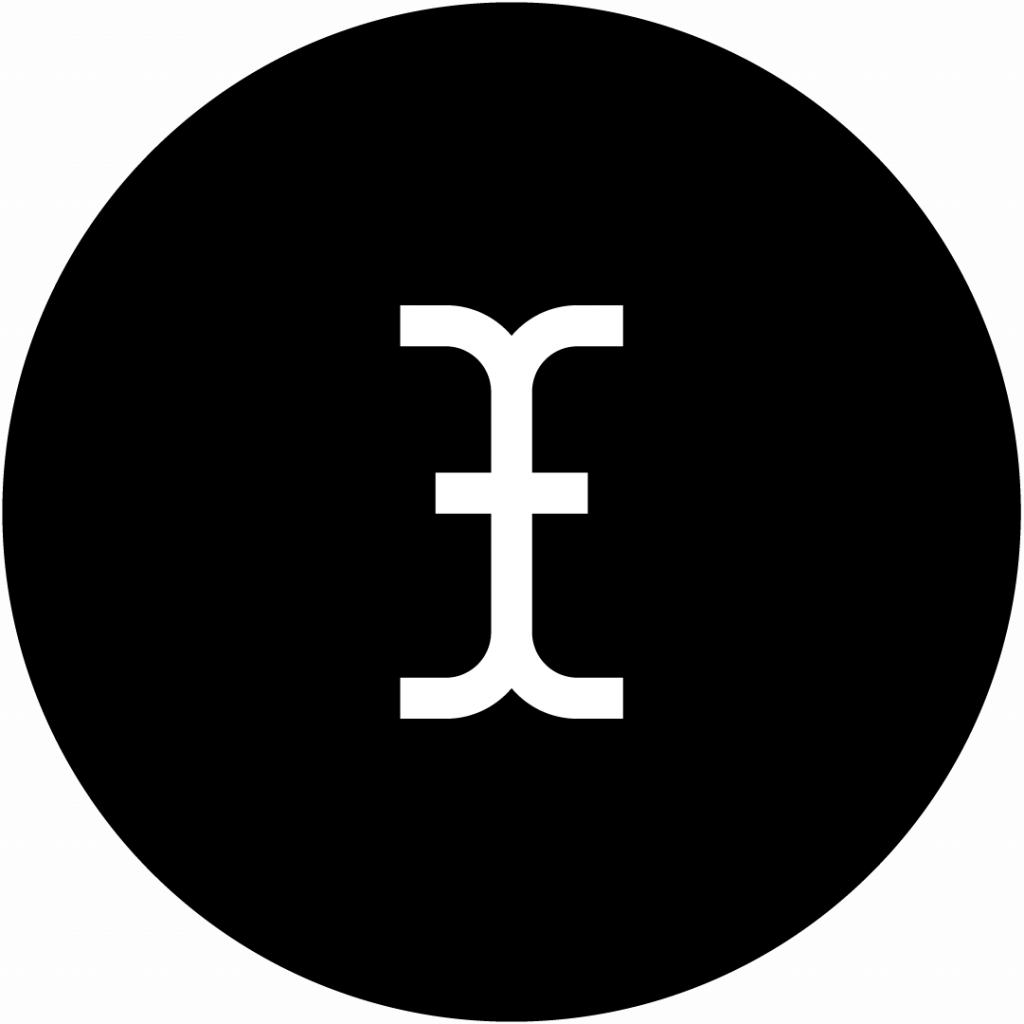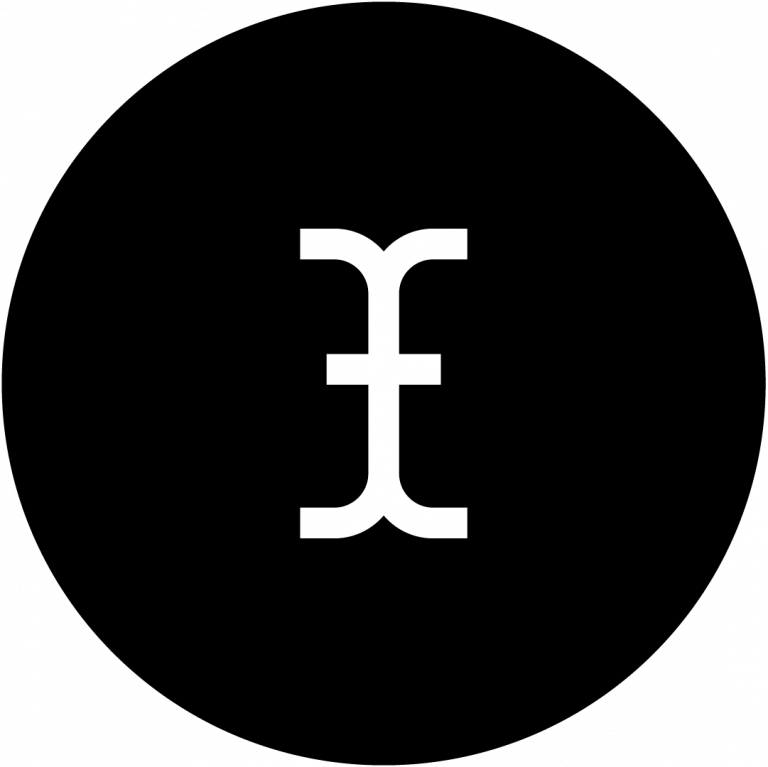Banyak hal yang berubah gara-gara Covid-19 mengguncang dunia. Bahkan, gaya hidup kita pun turut berubah karena harus menyesuaikan situasi dengan benda-benda yang tetiba jadi sering kita pakai secara intens. Nggak sedikit pula budget yang harus kita keluarkan demi memiliki barang-barang yang sepertinya ‘wajib’ kita miliki di era saat ini. Oops!
Tapi nggak semua benda-benda baru gara-gara Covid-19 ini benar-benar baru, lho. Justru nggak sedikit benda-benda di masa lalu hadir kembali demi kelangsungan hidup yang lebih aman setelah pandemi Covid-19.
Apa saja itu?
Sarung Tangan

Di tahun 1950-an, para wanita mengenakan sarung tangan agar terlihat glamor dan berkelas. Mereka mengenakan sarung tangan saat berjalan keliling kota, pergi ke gereja, jamuan makan, dansa, hingga ke restoran dan gedung pertunjukan.
Bahkan, konon katanya, wanita-wanita intelek selalu mengenakan sarung tangan saat berpergian dengan kereta, pesawat, dan kendaraan umum lainnya.
Sarung tangan di kala itu hanya dilepas ketika sudah duduk di meja makan sebuah restoran, sebelum makan, minum, merokok, bermain kartu, dan ber-make-up. Bahkan, ketika berjabat tangan, wanita tak dihendaki melepaskan sarung tangan ketika memakainya. Tentu saja kecuali jika yang dikenakan adalah sarung tangan berkebun, ya.
Tapi terbayang, kan, betapa higienisnya tangan di kala itu?
Untuk para wanita, agaknya, sarung tangan juga menjadi elemen penting yang masuk ke dalam daftar survival kit melawan penyakit yang dibawa oleh virus Corona ini.
Tak jarang, sekarang, kita melihat sejumlah orang mengenakan sarung tangan ke supermarket, pasar, atau sekadar terima paket belanja online di rumah. Pasalnya, penggunaan sarung tangan latex yang diperuntukkan bagi aktivitas medis kurang dianjurkan untuk dikenakan sehari-hari. Jadi, perlu juga, nih, sarung tangan kain yang fungsional apalagi stylish.
Sekarang, selain masker, mulai bermunculan lini lokal yang menawarkan sarung tangan sebagai produk baru mereka dalam koleksi gara-gara Covid-19 ini. Berbeda dengan sarung tangan zaman dulu yang dipadu-padankan dengan warna pakaian dan acara yang dihadiri, karena pandemi, sarung tangan zaman sekarang banyak yang dipasangkan serasi dengan masker kain dan fashionable.
Cubicle

Ingat, kan, kalau kantor-kantor tahun 1960 sampai 1990-an itu seperti apa? Ya, penuh dengan sekat alias cubical yang menjadi pembatas antar area kerja setiap karyawan.
Tujuan utama pengaplikasian sekat atau cubical ini adalah untuk peningkatan konsentrasi karyawan sehingga produktivitas pun meningkat. Selain itu, privasi setiap karyawan pun terdukung dengan sistem sekat ini.
Masing-masing karyawan memiliki area sendiri-sendiri sehingga bebas menentukan sisi mana untuk ia bekerja, menerima telepon, meletakkan alat-alat tulisnya, hingga benda-benda pribadinya. Saking pribadinya, ketika duduk di meja kerja, para karyawan bahkan tidak bisa melihat rekan sebelahnya.
Hingga di akhir tahun 1990-an dan 2000-an, meluaslah konsep desain open-space. Rumah, sekolah, restoran, hingga kantor berlomba-lomba mendobrak konsep cubical ini yang dianggap banyak membatasi ruang kreativitas.
Cubical dianggap “mengurung” ide-ide baru karyawan, membuat suasana kantor terasa kaku, tidak menyenangkan, minim interaksi, bahkan boros dalam segi pengeluaran perusahaan.
Konsep open-space jadi idola dimana-mana. Tidak ada lagi papan-papan sekat antar meja. Bahkan banyak kantor sampai-sampai meniadakan meja dan kursi kerja permanen untuk para karyawan. Setiap karyawan tinggal membawa laptop-nya dan bisa duduk dimanapun di area kantor tersebut. “Privasi hanya membatasi kreasi.” Begitu katanya.
Tapi gara-gara Covid-19, tidak sedikit outbreak terjadi di perkantoran. Perusahaan-perusahaan terkena dampak dari pandemi ini. Situasi kantor di dalam gedung dengan sirkulasi udara yang tidak alami atau hanya memakai AC ditambah konsep open-space memperburuk kejadian ini.
Kebebasan ruang gerak dan interaksi dari konsep open-space ini nyatanya juga memperbesar kemungkinan persebaran virus-virus di dalam ruang kerja.
Kini, para desainer interior dan arsitek banyak yang telah memberikan gambaran desain kantor masa depan selepas pandemi ini. Selain jarak yang diatur, sekat juga menjadi solusi sekaligus cara untuk memitigasi kejadian-kejadian serupa.
Kaca Nako

Kaca nako atau louvre window lumrah kita lihat di rumah-rumah tahun 1980 sampai 1990-an di Indonesia. Hingga perkembangan desain minimalis muncul dan terus berkembang, pilihan kaca nako lama-kelamaan seakan sirna. Media sirkulasi udara dan cahaya beralih ke jendela-jendela kaca besar dengan frame persegi.
Namun, salah satu kekurangan jendela besar adalah bukaannya yang tidak dapat diatur sefleksibel mungkin. Berbeda dengan kaca nako yang seluruh kacanya dapat dibuka tanpa harus membuka semuanya dalam satu bingkai sekaligus.
Gara-gara Covid-19, sirkulasi udara alami menjadi salah satu hal penting yang harus terjadi di dalam satu ruangan. Karakter kaca nako yang fleksibel dan memiliki ketahanan yang kokoh kembali dilirik belakangan ini.
Pembukaan kaca nako bisa disetel sedemikian rupa sehingga kamu tinggal membuka tutup dengan tuas atau penarik tertentu. Kaca nako seringnya hadir di dapur, teras, ataupun kamar mandi, karena memang kedua ruangan ini yang lebih sering berurusan dengan aliran udara dan bau tertentu.
Daripada repot memasang unit ventilasi, kaca nako bisa ditempatkan di bagian atas sebagai jalur keluar masuk udara paling praktis dan hemat. Meskipun lebih membutuhkan ketelitian ketika dibersihkan, kaca nako tetap mampu menjadi media sirkulasi udara dan cahaya yang cukup optimal.
Penutup Wajah

Tahu, kan, wanita-wanita elit zaman abad ke-19 juga gemar memakai topi atau head-piece dengan veil yang menutup wajahnya? Veil atau kerudung renda ini dikenakan para wanita modis untuk menutupi wajah mereka dari debu.
Hingga dalam sebuah artikel tahun 1878 yang dicetak di sebuah gazette rumah sakit dan di Scientific American, A.J. Jessup, seorang dokter di Westtown, New York, merekomendasikan masker katun untuk membatasi penularan selama epidemi.
Seiring perkembangan penelitian dan percobaan di sekian wabah yang terjadi, veil atau kerudung ini beralih lama-kelamaan menjadi masker untuk melindungi perawat dan ahli-ahli bedah selama operasi.
Hingga pada 1918 epidemi flu global terjadi, personel medis secara rutin mengadopsi masker untuk melindungi diri mereka sendiri dan banyak kota mengharuskan wargan mengenakannya di depan umum.
Di Seattle, lokasi trem mengharuskan semua pengendara memiliki masker, palang merah setempat mendaftarkan 120 pekerja untuk menghasilkan 260.000 masker dalam tiga hari. Kemudian dari sinilah kita melihat pelindung wajah lainnya termasuk face shield yang kita sedang cari-cari setelah pandemi Covid-19 ini.
Drive In Theater

Konsep drive-in theater dipelopori oleh seorang pemilik perusahaan kimia asal New Jersey, Richard M. Hollingshead. Dia membuka drive-in theater pertama di Camden, New Jersey, tepatnya pada 6 Juni 1933. Untuk menarik minat konsumen, Hollingshead memunculkan slogan “menerima seluruh anggota keluarga, tidak peduli seberapa berisik anak-anak” guna mempromosikan drive-in theater ini.
Model bioskop luar ruangan ini mencapai puncak kejayaannya pasca Perang Dunia II pada dekade 1950 hingga 1960. Dengan harga tiket masuk US $ 25 sen, para penonton sudah bisa menonton film di sebuah taman dengan layar raksasa, duduk di atas mobil mereka, merokok, minum bir, menikmati makanan ringan, dan menikmati udara segar.
Semua dilakukan dalam satu waktu bersama orang-orang terdekat, yang mereka perlu lakukan hanyalah memarkir mobilnya dengan tertib sesuai dengan titik-titik lokasi yang telah ditentukan. Era emas Hollywood di pertengahan abad 20 juga tidak lepas dari peran drive-in theater yang pada saat itu menyumbang lebih dari 4.000 layar di seluruh Negeri Paman Sam.
Kejayaan drive-in theater di AS juga diikuti oleh drive-in theater di negara-negara belahan dunia lainnya, diantaranya Australia, Italia, Kanada, dan Yunani. Di Indonesia sendiri, konsep ini telah menginspirasi hadirnya bioskop keliling, yang lebih kenal dengan sebutan layar tancap.
Popularitas bioskop drive-in meningkat di masa pasca-Perang Dunia II dan mengalami masa keemasan pada era 1950-an hingga 1960-an dengan 5.000 teater tersebar di seluruh AS. Namun dengan meningkatnya harga properti, terutama di kawasan pinggiran kota, ditambah meningkatnya jumlah bioskop konvensional serta menjamurnya tempat penyewaan video membuat industri drive-in terus menurun.
Beberapa waktu lalu, kita di Indonesia juga dikejutkan dengan berita akan adanya drive in theater. Munculnya drive in cinema ini menyusul adanya aturan physical distancing gara-gara Covid-19. Nggak sedikit meme dan konten di social media yang bercerita tentang kerinduan orang-orang akan menonton film di bioskop.
Tapi ternyata ini bukan hal baru. Ciputra pernah membangun teater kendara di Pantai Binaria (sekarang Ancol), Jakarta, pada 1 April 1970. Pembangunannya seiring dengan pengembangan Ancol sebagai daerah perumahan, industri, dan rekreasi oleh PT Pembangunan Jaya.
Ciputra memperoleh ide membangun teater kendara setelah melihatnya di New York, Amerika Serikat. Melihat kondisi pasar seperti itu, Ciputra tak ragu menghadirkan teater kendara pertama di Indonesia. Luasnya lima hektar dan mampu menampung 800 mobil.
Teater kendaraan terbesar di Asia Tenggara itu menghabiskan 20.000 meter kubik pasir, 10.000 meter kubik batu, 2.000 drum aspal, 200 meter kubik beton, dan 85 ton besi konstruksi. Alat-alat pemutar filmnya dibeli dari perusahaan Toshiba, Jepang.
Untuk semua pembangunan itu, Pembangunan Jaya mengeluarkan Rp260 juta, atau setara dengan Rp10.4 miliar nilai uang sekarang. Tapi Gubernur Jakarta waktu itu, Ali Sadikin, mengingatkan bahwa teater kendara sesungguhnya hanya untuk kaum the haves (orang berpunya) saja karena yang nonton cuma orang bermobil.
Untuk mengurangi kesan teater kendara hanya punya kaum the haves saja, Pembangunan Jaya menekan harga tiket. Hitungannya per orang, bukan per kendaraan. Dewasa kena Rp500, sedangkan anak-anak Rp300 atau senilai 1 dolar Amerika. Harga ini masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan penduduk Jakarta kala itu.
Furnitur Fiberglass

Di era abad pertengahan, dengan gaya Retro, furnitur-furnitur dengan warna pop menjadi tren di kala itu. Bukan hanya warnanya yang mencolok, material plastik dan fiberglass juga menjadi ciri khas desain furnitur di tahun 1950-an sampai 1970-an itu.
Plastik saat itu dianggap sebagai penemuan material yang menunjukkan cita rasa muda, praktis, bebas, dan kesan pendobrak tradisi. Salah satu ikon terbaik dari masa itu ialah deretan kursi karya Eames dari Vitra yang hingga kini masih memesona.
Pada tahun 2001, setelah material fiberglass dihentikan selama tahun 1980 karena masalah lingkungan, gaya kursi ini diperkenalkan kembali dengan cangkang terbuat dari polypropylene.
Bahan plastik baru ini dianggap lebih baik karena sepenuhnya dapat didaur ulang dan juga lebih murah. Namun, enggak sedikit kolektor yang melihat hanya versi fiberglass yang dianggap sebagai kursi “asli” meskipun versi plastik polypropylene yang lebih baru dibuat dengan baik dan diproduksi secara sah.
Model kursi Panton Chair ataupun DSW Chair juga banyak menginspirasi kursi-kursi untuk fasilitas publik. Stadion, ruang tunggu rumah sakit, hingga jok kendaraan umum bahkan memiliki citra yang serupa.
Hingga era post modern hadir dan gaya hidup masyarakat kian berkembang, kursi-kursi fiberglass lambat laun berganti ke kursi dengan bantalan kain, material logam, beton, dan lain sebagainya.
Ternyata gara-gara Covid-19 ini, berbagai fasilitas publik menjadi ‘sasaran’ perhatian agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Salah satunya adalah material furnitur yang dipakai di tempat umum harus memiliki ketahanan tangguh, tidak menjadi ‘rumah’ virus dan kuman, terlebih mudah dibersihkan dengan bahan kimia setelah digunakan.
Jadi sepertinya, fasilitas-fasilitas publik, seperti bank, rumah sakit, bandara, maupun ruang tunggu pusat perbelanjaan akan kembali diwarnai dengan furnitur-furnitur plastik ala abad pertengahan.
Ternyata benda-benda masa lalu yang sudah lama dilupakan justru memiliki peran penting di masa sekarang, ya. Atau terbalik. Justru dari dulu, orang-orang sudah lama mempersiapkan dan memproteksi diri untuk resiko-resiko buruk yang dapat menimpa kesehatan.
Apapun itu alasannya, sesungguhnya tidak ada gaya atau tren yang hanya berlaku di satu masa. Perkembangan zaman, teknologi, gaya hidup, kejadian-kejadian di masyarakat turut memutar roda gaya desain dengan tujuan utamanya, yaitu menjadi solusi dalam setiap hidup manusia di setiap zaman.