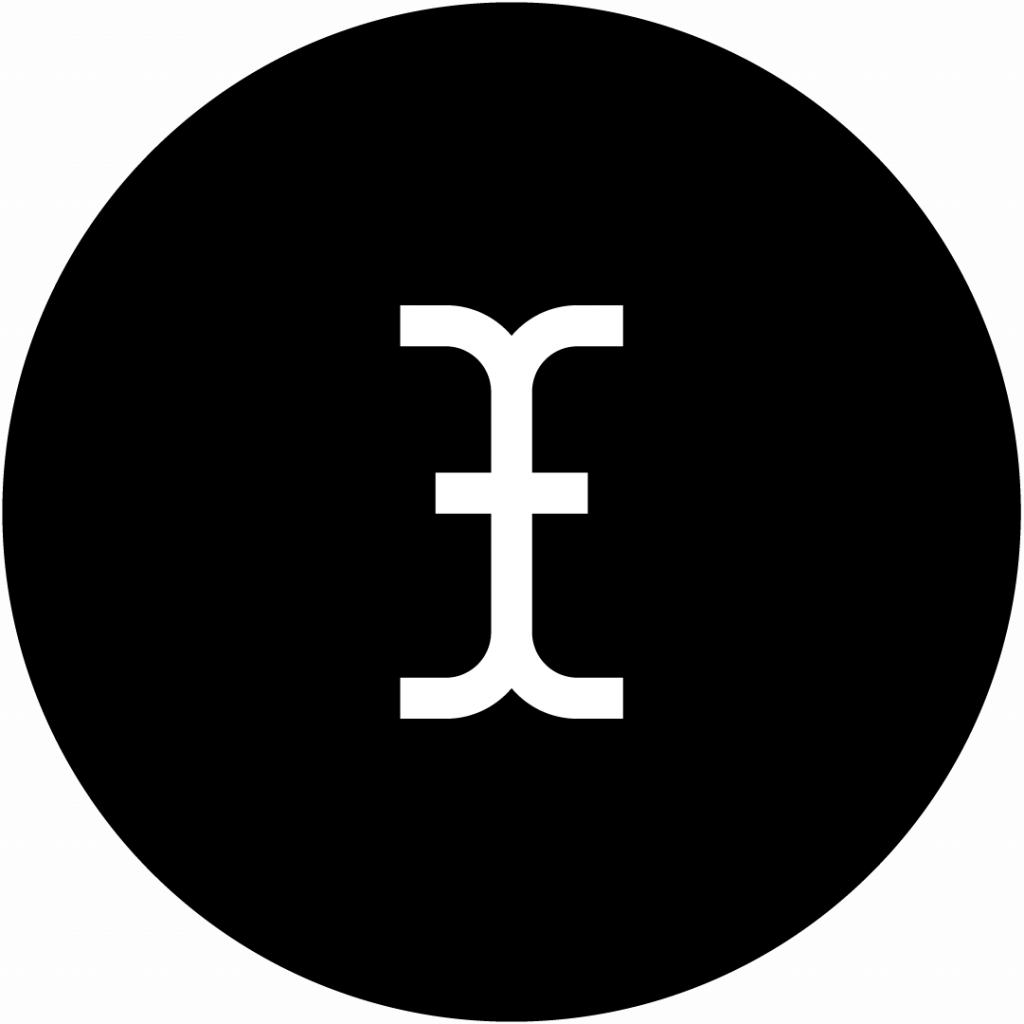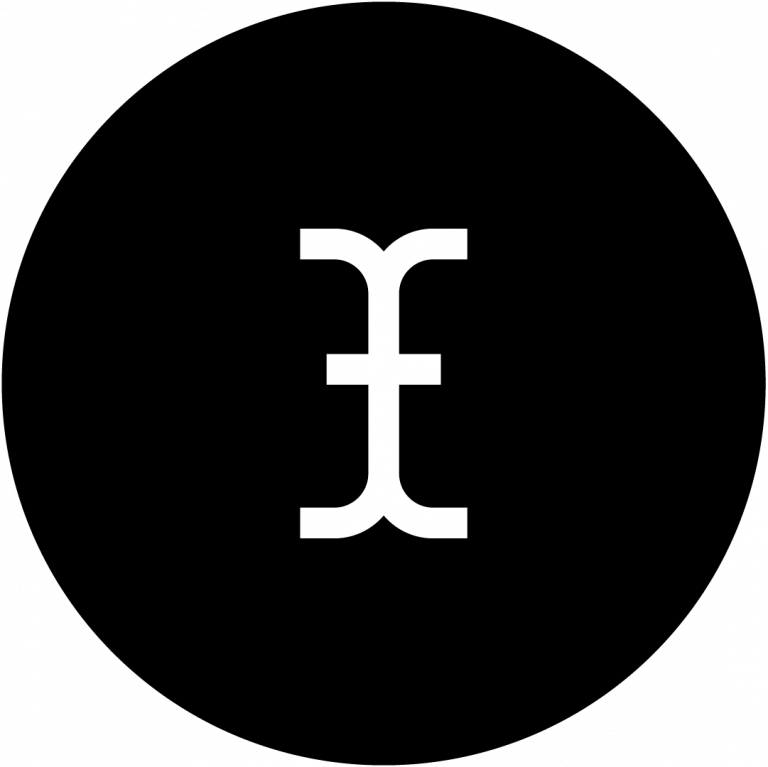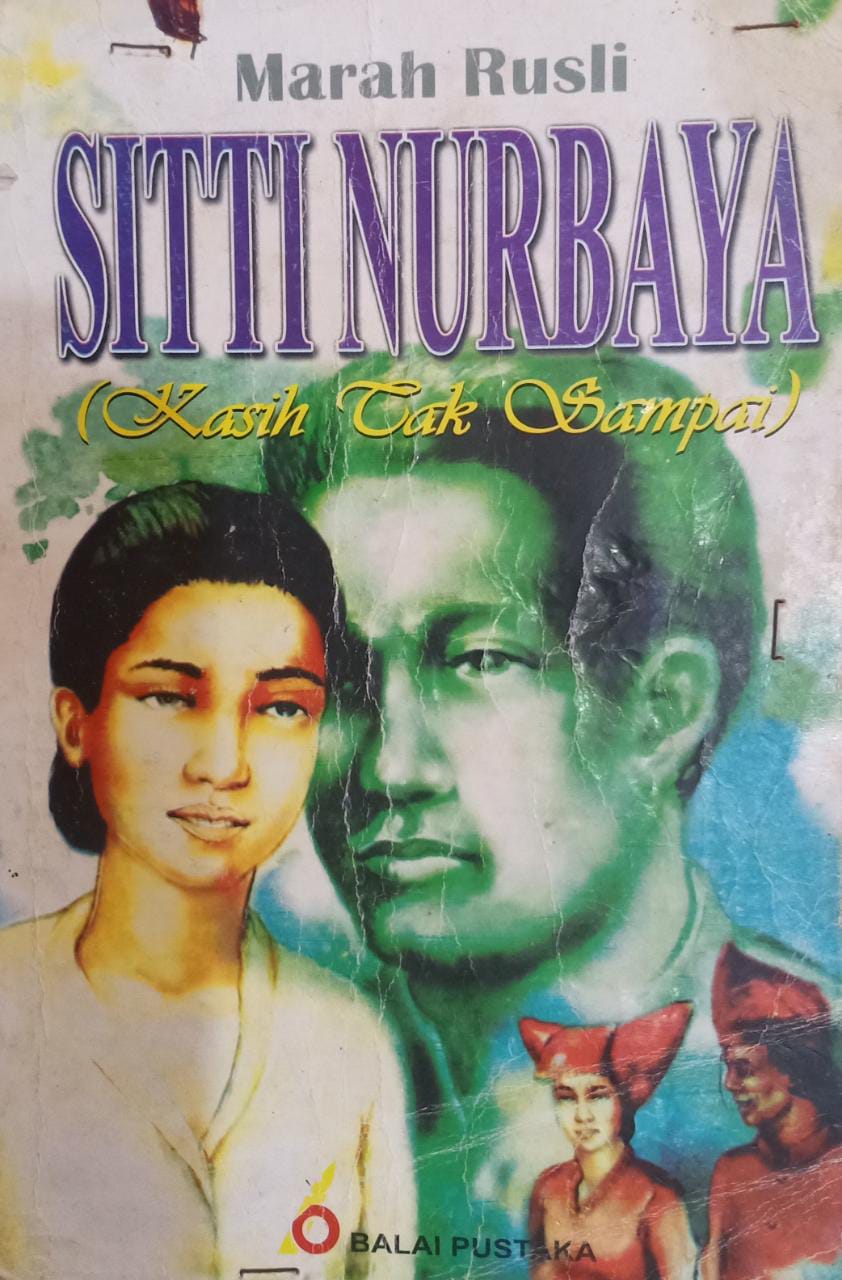
Meskipun ketenaran tidak mendunia, tetapi karya sastra klasik Indonesia tidak bisa diremehkan. Novel-novel klasik Indonesia banyak menggali berbagai tema baik yang mencerminkan adat istiadat budaya atau pemikiran modern yang memantulkan hasrat kebebasan berpendapat.
Salah satu fungsi dalam kegiatan membaca adalah untuk mengetahui isi pikiran manusia di masa dia hidup. Dan di awal perkembangan sastra Indonesia, isi pikiran tersebut banyak tertuang oleh penulis-penulis asal Sumatra Barat.
Apa alasannya?
Budaya Egaliter Sumatra Barat
Mengapa pada awalnya penulis Indonesia mayoritas didominasi oleh anak Minang bisa dirujuk pada “jiwa pemberontak” suku Minangkabau. Sistem kemasyarakatan yang egaliter menyalurkan rasa kesetaraan yang tidak membedakan antara orang kecil dan petinggi sehingga tingkat pendidikan pun cenderung merata juga.
“Iklim budaya egaliter dan antiprimordialisme masyarakat Minangkabau tidak dapat dikesampingkan dalam membentuk watak kepengarangan para sastrawannya,” ungkap ungkap Dr Harris Effendi Thahar, Sastrawan dan ketua Dewan Kesenian Sumatra Barat.
“Artinya, tanpa dipupuk pun, ranah Minangkabau tetap melahirkan para penulis bermutu dan sastrawan yang membanggakan, dari zaman ke zaman.”
Sifat egaliter inilah yang memicu aspirasi untuk jadi masyarakat yang maju. Mereka menentang kolonialisme dan pada saat yang bersamaan juga menerima pembaharuan gaya hidup yang terlepas dari kekangan tradisi. S
eperti novel Sitti Nurbaya (1922) karangan Marah Rusli yang dianggap sebagai salah satu pelopor novel roman Indonesia. Secara tidak langsung novel roman ini mengkritik keputusan sang tokoh utama yang rela dipinang oleh Datuk Maranggih, lelaki yang jauh lebih tua, demi meringankan beban utang keluarga.
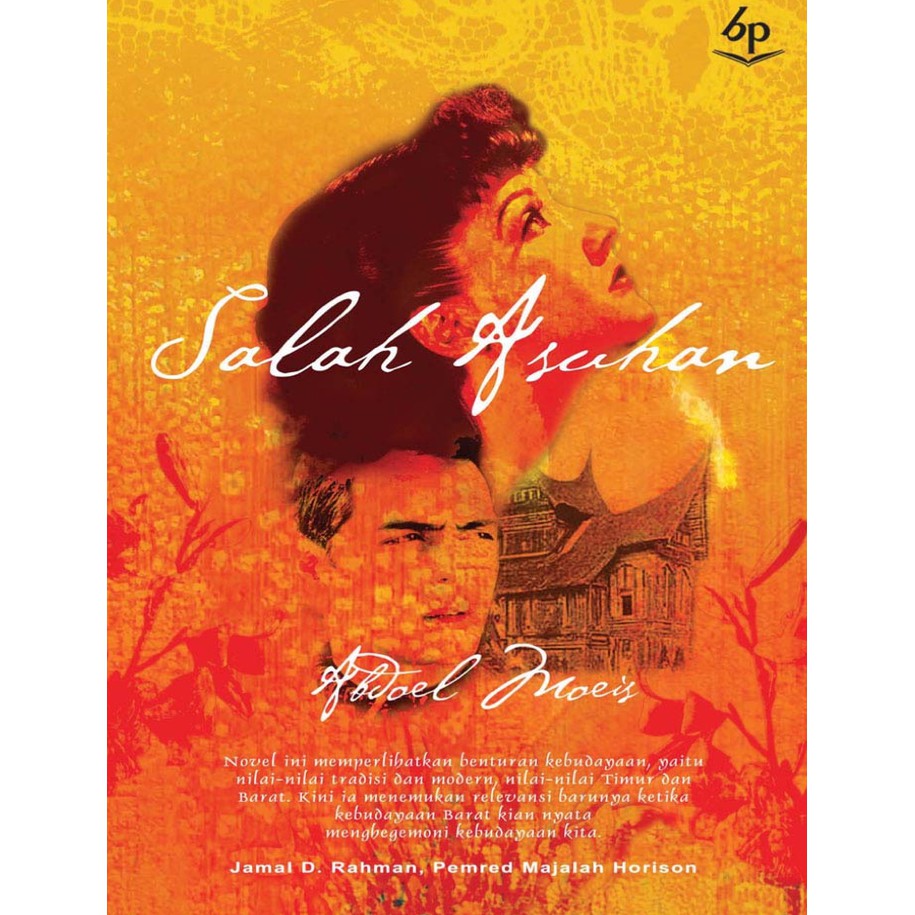
Kalau jalan cerita Sitti Nurbaya masih dalam ruang lingkup budaya, maka Abdul Moeis menyodorkan plot roman yang lebih modern dengan Salah Asuhan (1928). Tokoh utamanya, Hanafi, setelah menceraikan Rapiah, gadis yang ia nikahi lebih karena membalas budi jasa mamaknya (paman), kemudian menjalin kasih dengan perempuan blasteran Prancis.
Isu pertentangan tradisi yang dipandang kuno juga jadi topik sentral dalam Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (1937) karya Hamka yang mengangkat tema kawin paksa.
Yang menarik, penulis Sumatra Barat, meskipun didominasi oleh pria, kadang juga mengedepankan sosok perempuan kompleks lengkap dengan rangkaian tantangan yang mereka hadapi sebagai perempuan.
Seperti Layar Terkembang (1937) karya Sutan Takdir Alisjahbana yang memiliki dua tokoh perempuan bersaudara, Tuti dan Maria, yang sama-sama mahasiswi kedokteran. Tuti lebih free spirit sementara Maria cenderung serius, tetapi mereka menghadapi dinamika kehidupan yang serupa, baik soal cinta, karier, dan tuntutan keluarga. Gambaran utama yang diberikan dari Layar Terkembang adalah bagaimana kedua perempuan berpendidikan ini mengadopsi—dan beradaptasi dengan—gaya hidup yang modern, terutama karena mereka merantau ke Batavia (novel karangan penulis Minang pertama yang ber-setting di luar tanah kelahiran).
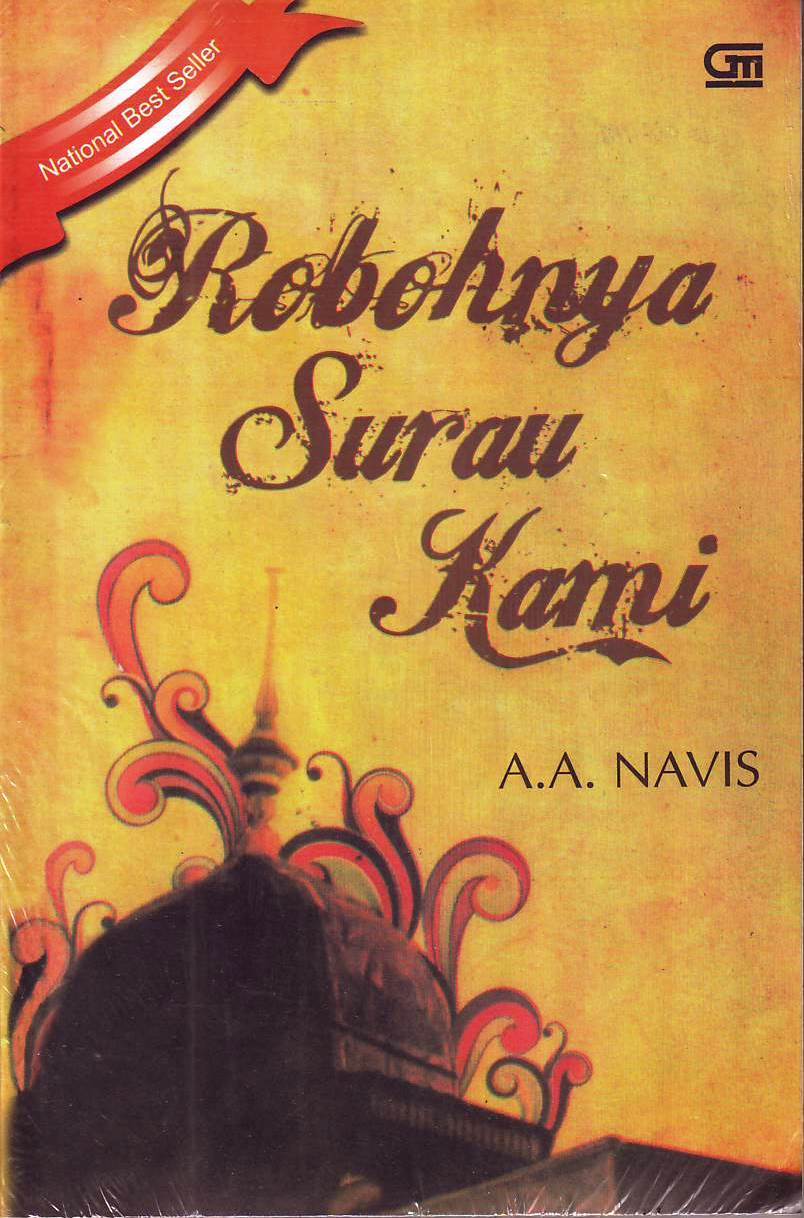
Penyesuaian interpretasi akan ajaran agama juga tak luput dari perhatian penulis keturunan Minangkabau. AA Navis melalui cerpen—dan antologi cerpen—Robohnya Surau Kami (1956) jadi contoh utama dengan cerita yang menyindir sifat religius berlebihan, yang tidak melibatkan bakti amal kepada sesama manusia. AA Navis sendiri tidak pernah menyinggung isu tradisi dalam ceritanya karena ia lebih tertarik dan prihatin kepada isu-isu kemanusiaan.
Masih banyak lagi sastrawan-sastrawan asal Sumatra Barat yang berhasil mencetak jejak sastra yang mendalam. Sebut saja Idrus (Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma), Nur Sutan Iskandar (Katak Hendak Jadi Lembu), Chairil Anwar (Aku Ini Binatang Jalang), Armijn Pane (Belenggu), dan Sariamin Ismail (Kalau Tak Untung). Penulis terakhir ini merupakan novelis perempuan Indonesia pertama dan ia kerap menggunakan pseudonim Selasih untuk penulisan novel.

Ahli Bahasa
Peluang pendidikan yang merata jadi salah satu alasan mengapa dunia sastra banyak dipopulasi oleh orang Sumatra Barat. Bahkan mereka pun yang mendorong evolusi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia.
Sutan Takdir Alisjahbana merupakan seorang ahli tata bahasa yang menerbitkan buku Tata Bahasa Baru Indonesia (1936) dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk memodernisasi bahasa; sementara Sutan Muhammad Zain menulis buku Djalan Bahasa Indonesia dan Kamus Modern Bahasa Indonesia yang mnjadi panduan peralihan gramatikal Melayu ke Indonesia.
Singkatnya penulis-penulis Minangkabau banyak berkontribusi terhadap perkembangan dunia sastra Indonesia. Saat ini masih ada beberapa penulis muda asal Sumatra Barat yang menjanjikan, seperti Boy Candra (Origami Hati) dan Hasbunallah Haris (yang tahun lalu menulis novel berbahasa Minangkabau berjudul Mandulang Cinto). Namun sulit untuk melampaui pencapaian pendahulu mereka, terlebih karena era telah berubah.
Sikap kritis akan tradisi para sastrawan Sumatra Barat masa lalu, yang disertai dengan hasrat tinggi untuk bebas dan beradaptasi dengan perubahan zaman, ampuh melahirkan karya-karya seni sastra modern yang hingga saat ini tetap relevan dan relatable.