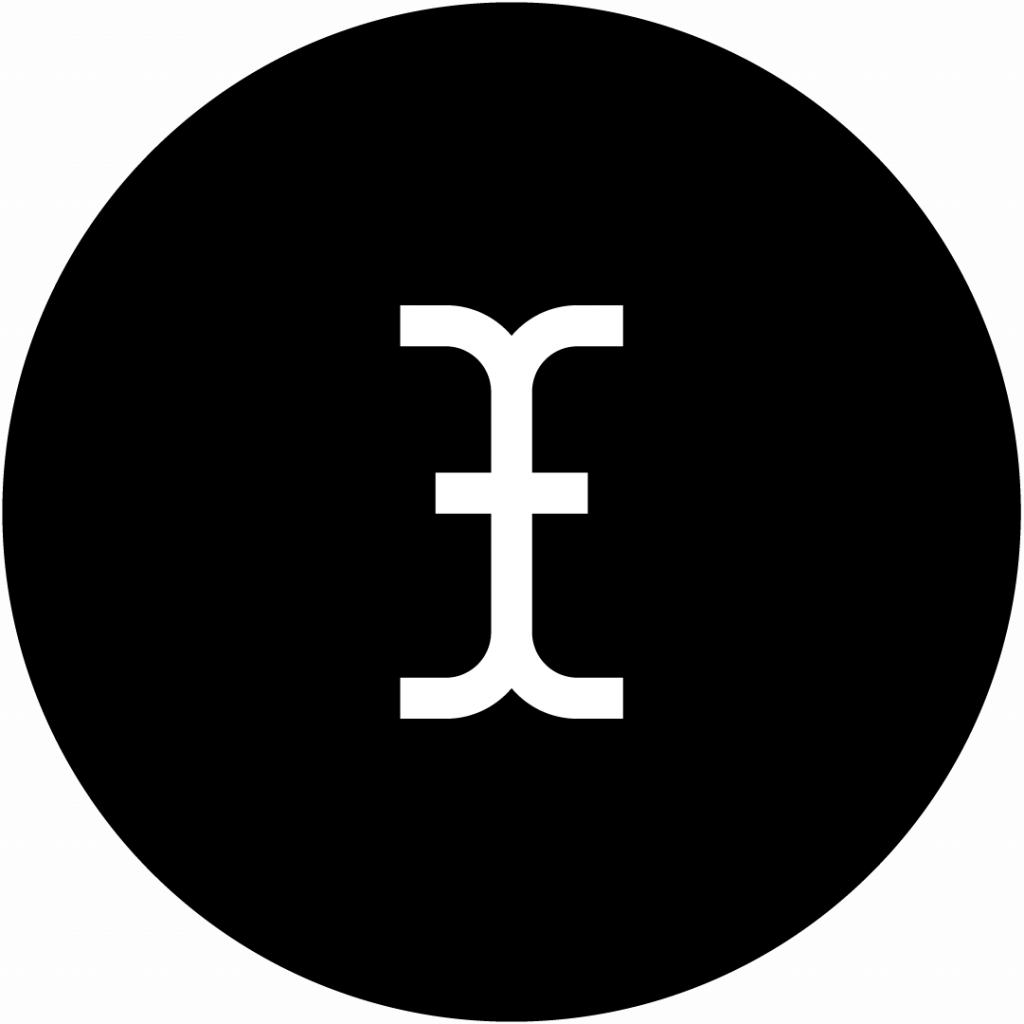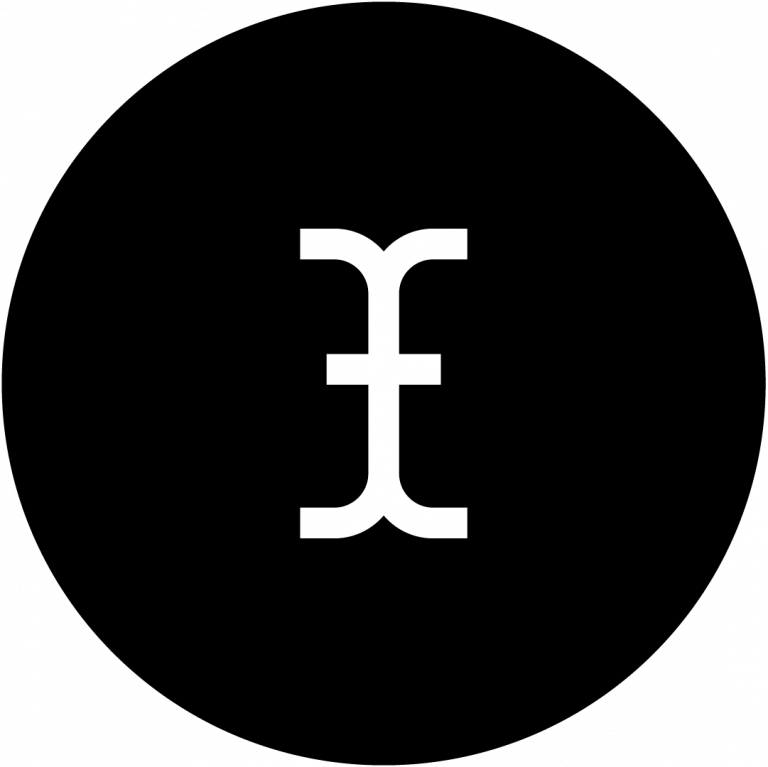Pernahkah kamu dulu saat hari raya seperti Natal dilayangkan surat berisi kartu-kartu hari raya yang digambar oleh orang-orang penyandang disabilitas?
Surat tersebut berasal dari yayasan yang menaungi para seniman dengan disabilitas itu. Kamu akan dibuat takjub akan kehebatan desain seniman yang tak ciut atas keterbatasan fisik. Mereka tak memiliki tangan lantas mereka pun melatih diri menggambar dengan jemari kaki. We’re sold!
Sayangnya, wawasan kita akan seniman penyandang disabilitas terkadang stop hanya sampai di situ. Dunia seni, yang notabene berawal dari buah pikiran terlepas dari kemampuan fisik, selama cenderung ekslusif, jarang inklusif—terutama terhadap seniman penyandang disabilitas.
Lengan Terkembang
Walau begitu bukan berarti tak ada figur atau organisasi yang tidak memberikan platform bagi seniman dengan disabilitas. Baru-baru ini, Yayasan Selasar Sunaryo berkolaborasi dengan Kelompok Kepakaran Estetika dan Ilmu Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain untuk menggelar seminar bertajuk Lengan Terkembang. Mereka menyorot soal ruang seni yang masih belum inklusif terhadap seniman dengan disabilitas.
“Program pendidikan seperti pameran keliling, workshop, dan artist talk masih minim inovasi, dan belum mengutamakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang juga berhak mendapatkan pendidikan melalui seni,” ungkap Agung dari Yayasan Selasar Sunaryo.
Padahal, berbicara soal sejarah seniman difabel, ada beberapa seniman legendaris mancanegara yang tetap berkarya meski memiliki keterbatasan fisik. Sebut saja Beethoven yang meskipun daya pendengarannya redup sejak ia berusia 26 tahun tetap produktif menciptakan musik dan simfoni.
Atau pelukis asal Prancis, Henri Matisse, yang daya fisik tubuhnya melemah dan mesti menggunakan kursi roda setelah ia terkena kanker di usia senja. Ia lantas beradaptasi dengan kondisi tubuhnya dan berganti menekuni seni decoupage, (seni kolase menggunakan kertas), yang lebih mudah ia lakukan.

Ableism
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seniman difabel senantiasa jadi afterthought hingga kini. Pertama, akses dan fasilitas. Serial hit Netflix, Sex Education, sempat selintas membahas soal ini di season 4: ketika seorang murid dengan kursi roda komplain atas lift kampus yang selalu rusak membuatnya tak bisa mengakses kelas semudah mereka yang masih bisa naik tangga.
Apakah sekolah seni dan galeri seni selama ini telah mengakomodasi akses dan fasilitas yang bisa memudahkan seniman dengan disabilitas mengakses pendidikan?
Kedua, adalah perilaku masyarakat. Tak hanya di dunia seni, kerap masyarakat secara umum masih menganggap orang dengan disabilitas sebagai seseorang yang “other than..”, atau yang disebut juga dengan ableism, yaitu memandang rendah atau kasihan kepada penyandang disabilitas.
Itulah cara pandang tak sadar yang membuat kita memutuskan untuk membeli kartu-kartu hari raya yang digambar oleh seniman dengan disabilitas.
“Ableism memberikan impresi ke dalam alam bawah sadar seseorang di mana seakan-akan ada standar kemanusiaan, dan yang tak jatuh ke dalam standar tersebut jadi tidak benar,” ujar Slamet Tohari, pendiri Pusat Studi dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya, seperti dilansir trf.news.
Menariknya, mungkin dalam upaya mereka untuk fit in, seniman penyandang disabilitas pun terkadang mencoba untuk mengikuti standar tersebut dengan menciptakan karya seolah mereka tak memiliki disabilitas.
“Karena seni sangat ekslusif, penyandang disabilitas juga menggunakan logika orang tanpa disabilitas,” lanjut Slamet. “Sebagai contoh, saya pernah membaca puisi yang ditulis oleh seseorang yang buta. Mereka menulis bulan yang bercahaya.”
Ironisnya, seniman penyandang disabilitas kerap dielu-elukan terlalu berlebihan. Yang kembali ke perilaku masyarakat yang cenderung mengasihani penyandang disabilitas. Menurut hasil studi Mapping Art and Disabilities in Indonesia yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya dan British Council, “Rasa iba, sejauh ini, menempatkan penyandang disabilitas dalam posisi yang tidak layak, menjadikan mereka sebagai alat untuk menguras air mata dan mengobjektifikasi seniman penyandang disabilitas.”
Lalu, apa solusi agar dunia seni bisa lebih inklusif kepada seniman difabel? Tiga yang terpenting: akses, fasilitas, dan keterlibatan.
Akses terhadap peluang pendidikan apapun itu formatnya, fasilitas yang memudahkan seniman penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan tersebut (penerjemah bahasa isyarat yang kini sering kita lihat di televisi adalah langkah yang efektif), dan keterlibatan dalam kegiatan serta pembuatan kebijakan. Karena pada akhirnya, mereka sendiri yang lebih tahu akan apa yang mereka butuhkan.